Entah apa yang dimau oleh pengatur semesta, selama seharian
penuh Niko Fischer terus saja mengalami kesialan. Mulai dari pagi hari, ia
diusir dari rumah kekasihnya karena salah paham. Niko menolak ajakan sang
kekasih untuk menikmati pagi lebih lama berdua karena banyak urusan yang mesti
dilakukan, tapi ia tak bisa menjelaskan. Hingga sepanjang hari, Niko tak bisa
mendapatkan segelas pun kopi untuk diminum.
Perihal apa yang ingin dilakukan dalam hidupnya, Niko memang
tak punya penjelasan. Ia seorang mahasiswa yang sudah dua tahun drop out dari Sekolah Tinggi Hukum di
Berlin, Jerman dan harus menemui psikolog untuk dibuatkan analisis kejiwaan
terkait pembatalan izin mengemudi. Bagaimana tidak, ia mabuk di jalan, saat sedang
mengendarai mobil.
Sekali lagi, Niko memang tak punya penjelasan atas apa yang
dilakukan dalam hidupnya. Sebab, ia pun menjalani semua tanpa tujuan. Oleh karena
itu, ia tak risau saat dikeluarkan dari kampus, Niko tidak pernah merasa
tertarik dengan kuliah hukum.
Kisah pemuda tanpa tujuan hidup ini menampakkan sebuah
anomali di negara maju seperti Jerman. Dimana semua orang dan segala urusan
berjalan teratur, rapi dan tepat waktu. Namun, ada seorang pemuda anak dari
pengacara kenamaan tumbuh tanpa tujuan hidup. Kerjanya hanya berkeliling kota,
luntang-lantung tanpa pekerjaan.
Sebagaimana sebuah anomali, bisa jadi kisah ini memang hanya
ada dalam film besutan Sutradara Jan Ole Gerster berjudul Oh Boy. Melalui kisah Niko Fischer yang diperankan oleh Tom
Schilling, Gerster mengajak kita untuk mengarungi kisah yang tidak lazim
terjadi pada pemuda Jerman.
Film berdurasi 88 menit ini mengisahkan 24 jam yang menjadi
titik balik dalam hidup pemeran utamanya. Niko baru merasa hidupnya ‘terusik’
saat ayahnya, Walter Fischer (Ulrich Noethen) tidak lagi mengirimkan uang ke
rekeningnya. Lalu, pertemuan dengan beberapa orang baru dalam seharian penuh
itu berhasil membuka cakrawalanya bahwa dunia ini luas, pun dengan
permasalahannya.
Pertama, ia mesti bertemu dengan psikolog (Andreas
Schroders) karena dianggap punya gangguan kejiwaan saat melanggar peraturan tak
boleh mabuk saat mengemudi. Dalam scene
ini, Niko dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, ada nilai, norma
dan peraturan yang membatasi tindak-tanduk warga kota Berlin.
Kedua, sepulang dari kantor psikolog, Niko dikejutkan dengan
kedatangan tetangga baru di apartemennya, Karl Speckenbach (Justus von
Dohnanyi). Awalnya hanya memberikan semangkuk bakso untuk tanda perkenalan,
namun tiba-tiba saja ia menangis tersedu di pundak Niko. Sambil terisak,
Speckenbach mengutarakan bahwa ia mengalami masalah seksual tak tertahankan. Istrinya
divonis menderita kanker payudara, untuk alasan kesehatan bagian tubuhnya itu
mesti diangkat.
Ketiga, di sebuah kafe Niko bertemu dengan teman sekolahnya,
Julika Hoffmann (Friederike Kempter). Awalnya, Niko tak mengenali Julika yang
tiba-tiba saja menyapanya. Sebab, penampilan Julika berubah drastis. Di masa
sekolah, Julika adalah gadis bertubuh gendut yang sering diejek
teman-temannya, termasuk Niko. Ia biasa dipanggil Gay Julika atau Elephant Girl.
Namun, kini Julika bertubuh langsing, tinggi semampai, berprofesi sebagai
pemain teater surealis.
Penampilan baru Julika membuat Niko tertarik. Dalam beberapa
jam saja, mereka saling mengenal lebih dekat. Julika banyak bercerita usaha
keras untuk mengecilkan tubuh. Ada pengalaman traumatis yang disimpan Julika
atas masa kecilnya.
Ketertarikan fisik pun muncul diantara keduanya. Hampir saja
Niko dan Julika berhubungan seksual. Namun Niko menolak saat ia tahu motif
Julika adalah balas dendam masa lalu. Ia ingin dapat pengakuan bahwa seorang
perempuan bertubuh gendut dan tidak menarik pun bisa menaklukkan seorang pria
tampan.
Jelang malam, Niko bertemu orang keempat yang memberi
pengaruh paling besar dalam mengacak-acak konsep hidup tanpa tujuannya selama
ini. Dialah seorang kakek tua (Michael Gwisdek) menghampiri Niko di sebuah bar
lalu bercerita panjang tentang masa kecil dan masa lalu bar yang sedang mereka
duduki.
Ceritanya sederhana, kakek itu suka bersepeda di sepanjang
jalan yang kini dibangun bar. Ia tidak pernah ambil pusing saat orang-orang
mengejeknya di jalan waktu ia mengendarai sepeda yang ukurannya terlalu besar
untuk tubuhnya yang kecil. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa tetap
bersepeda dan membuat orang lain bahagia walaupun dengan cara menertawakannya.
Sampai suatu ketika, jalan tersebut hancur, dipenuhi pecahan
kaca hasil perbuatan warga setempat (termasuk ayah sang kakek) yang menimpuki
kaca pertokoan. Aku menangis, kata sang kakek, karena apapun yang sudah terjadi
disana, dengan pecahan kaca memenuhi jalan seperti ini aku tak akan bisa
bersepeda lagi.
Usai menghabiskan ceritanya, habis pula kisah hidup sang
kakek. Saat berjalan keluar bar, ia jatuh terkapar di depan pintu. Sontak Niko
menolongnya, memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Mungkin, itu
kali pertama dalam hidup Niko merasa punya tanggung jawab atas sesuatu. Meski tak
mengenal, bahkan nama panggilan sang kakek, ia merelakan diri mendampingi
semalaman hingga dokter selesai menangani sakit kakek itu.
Film ini berakhir tanpa memberi tahu apa yang terjadi pada Niko
Fischer sesudah menjalani 24 jam yang membuat hidupnya sedikit guncang. Hanya satu
yang ditampilkan, di hari berikutnya Niko berhasil minum segelas kopi di sebuah
kafe. Hal biasa yang tidak bisa didapatnya selama sehari penuh dan seakan jadi
plot dalam film ini.
Namun, ekspresi sendu dari Tom Schilling serta gambar film
yang hitam putih berhasil menyampaikan pesan perenungan hidup para tokoh dalam Oh Boy. Alunan musik Jazz dari The Major
Minors dan Cherilyn MacNeil di sepanjang film pun berhasil menunjukkan bahwa pergulatan
manusia dalam mencari tempat yang tepat untuk hidupnya di dunia ini, selamanya
mungkin dilakukan. Sebagaimana lagu-lagu yang indah dan tak pernah usang tak
lekang oleh zaman.
Selain itu, Oh Boy juga
menampilkan tata kota Berlin secara detil. Mulai dari penempatan bangunan
kantor, tempat tinggal, taman kota, pabrik, jalur kereta api, trem, penempatan
lampu merah, dan perangkat kota lainnya. Menonton film ini anda dapat memahami tata
kota Berlin yang legendaris dalam seketika. Sebagai ibukota negara, memang wajar
bila kota ini nampak penuh dengan infrastruktur penunjang kehidupan negara dan
masyarakat. Namun semua tersusun dengan teratur dan rapi. Nampak dewasa dengan
segala kewibawaan.
Bertolak belakang dengan karakter Niko Fischer yang nampak
sedang diejek oleh judul film yang ia merupakan tokoh utamanya. Oh Boy. Ya, Niko benar-benar masih seorang
anak lelaki kecil yang malas untuk memikirkan hidup. Semoga 24 jam penuh
pengalaman itu bisa membuatnya beranjak!
Kurnia Yunita Rahayu
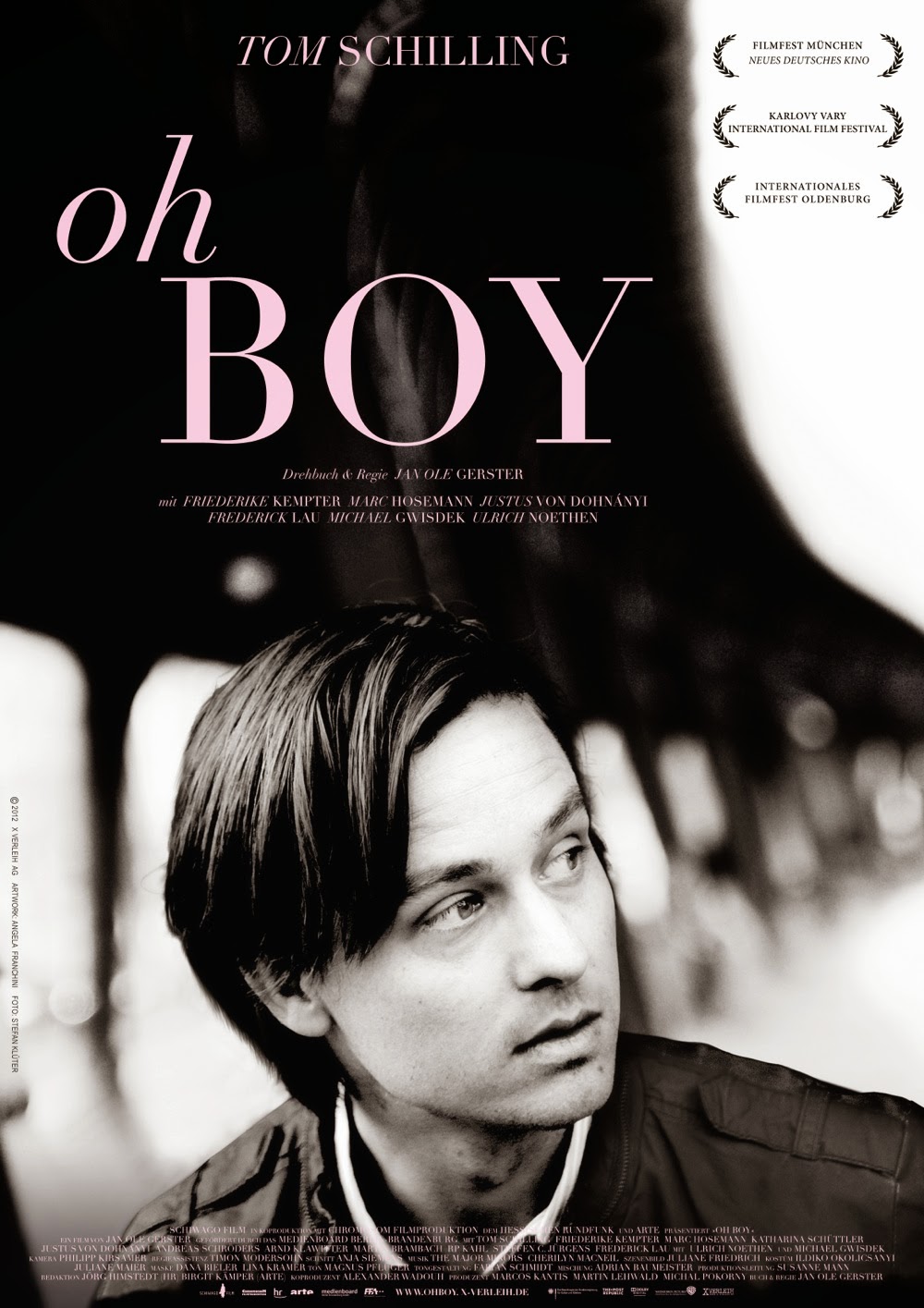
.JPG)

